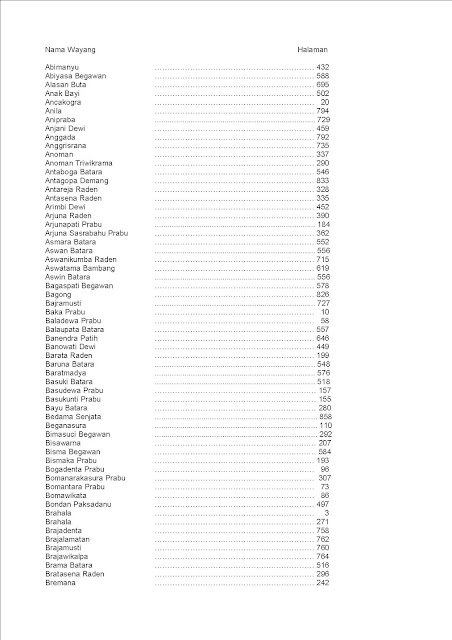Senin, 16 Juli 2012
KATA PENGANTAR
Sungguh
suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya karena telah berkesempatan membuat
wayang kulit dengan mempola/corekan (bahasa Jawa) sendiri, yang hal ini
merupakan kegemaran saya sejak saya masih anak-anak. Di samping kesempatan
memfoto sekaligus membukukan. Walaupun ada juga beberapa wayang yang saya peroleh
dari para seniman dan perajin wayang di daerah Surakarta
dan Jakarta.
Sepantasnyalah
terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada:
Pertama, almarhum Ki
Redigito, bapak saudara F.Sugiri (Museum SENAWANGI Jakarta Kota), yang
telah banyak memberikan petunjuk dalam membuat pola/corekan di kulit sebelum
ditatah.
Kedua, saudara F.Sugiri
sendiri, karena beliaulah saya berkesempatan memperoleh informasi-informasi
dari kepustakaan wayang yang ada di museum SENAWANGI Jakarta Kota.
Ketiga, almarhum saudara Djumadi,
penyungging wayang terbaik di Pasar Seni Jaya Ancol, karena beliaulah saya
mendapatkan petunjuk dalam teknis penyunggingan wayang.
Keempat, saudara Biman,
penyungging wayang terbaik di desa seni TMII, atas segala bantuannya dalam
mencarikan penyungging dan cempurit/gapit wayang yang baik sehingga wayang ini
selesai dibuat.
Kelima, para penatah
(khususnya almarhum saudara Supardi) dan penyungging (saudara
Sumanto, Kasidi, Hasan, Wadi,
Maryadi dll) serta semua pihak yang telah membantu pembuatan
wayang kulit purwa gaya Surakarta ini.
Keenam, saudara Nugrahani Indra S., S. Kom.,
ahli komputer di PERTAMINA Maritime Training Center, yang telah membantu
memindahkan tulisan ini dari program Word
Star ke program Office™.
Bahan-bahan yang
dipergunakan dalam pembuatan wayang ini adalah:
Kulit kerbau, saya peroleh dari almarhum
saudara Mardjijo, dukuh Gebangan, desa Nglebak, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta dan saudara Suprihono, Gendeng,
Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.
Cempurit tanduk kerbau bule
saya peroleh dari almarhum saudara Redjo Ngalimin, dan putrinya
mbak Awitini
dukuh Kuwel, desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
Gegel Kuningan dan Tuding Bambu
saya peroleh dari Ki Sutadi, desa Grasak, Gondang, Kabupaten
Sragen.
Pewarna, cat air Sakura Poster
Color dan bahan sablon dilarutkan dalam rakol cair.
Warna Emas, dari kepingan
prada/kimpok (bahasa Cina), saya peroleh dari toko obat Cina, Bintang
Terang, Glodok Jakarta Kota.
Jumlah
koleksi wayang ini sebanyak lebih dari 500 buah, di mana saya sendiri yang mengeluk,
memasang cempurit/gapitnya. Dengan panjang simpingan lebih dari tujuh setengah
meter di masing-masing sisi (pernah saya coba perdana dengan Dalang Ki Manteb
Sudharsono), dan wayang-wayang ini akan saya tunjukkan seluruhnya dalam buku
sekecil ini, di mana meliputi wayang-wayang simpingan dan dudahan, sehingga akan
menambah tebalnya buku. Namun dari sejumlah itu, saya rasakan masih kurang
lengkap. Mengingat banyaknya tokoh wayang yang belum sempat saya buat. Hal ini
dikarenakan: dalam pakeliran-pakeliran wujud sebenarnya tokoh-tokoh wayang yang
kurang banyak dikenal/kurang populer/kurang dianggap baku jarang dibuat orang
dan jarang ditunjukkan dalam pakeliran sehingga saya sulit memperoleh bahan
referensi (wayang-wayang tersebut sering digantikan wayang lain atau wayang srambahan,
ujud sebenarnya tidak pernah ditampilkan di kelir). Walaupun tidak sedikit pula
bahan referensi saya peroleh dari internet, face book dari para Dalang, pemikir, kreator, penggemar dan
pencinta wayang yang telah banyak menampilkan koleksi wayangnya sehingga saya
dapat membuat sket/ corekan tokoh-tokoh yang demikian. Namun demikian saya masih
harus banyak juga menafsirkan wayang-wayang yang tidak popular, wayang-wayang
yang dalam cerita sekali keluar langsung mati. Di samping keterbatasan dana dan
waktu pulalah yang mengharuskan saya terbatas juga dalam melengkapi jumlah
wayang ini. Walaupun saya telah membuat wayang satu demi satu dalam waktu tidak
kurang dari 30 tahun.
Akhir kata, tiada gading yang tak retak, demikian juga dalam buku ini. Oleh
karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun, saya terima dengan
senang hati.
Jakarta, 16 Juli 2008
Penyunting:
SUWADI KRIJO TARUNO
PENDAHULUAN
Pertunjukan
wayang sampai kini telah berumur lebih dari 3000 tahun, karena timbulnya wayang
pada sekitar 1500 sM, demikian menurut
Ir. Sri Mulyono. Bentuk wayang pada permulaannya tentunya tidak seperti bentuk
wayang yang sekarang ini, maksud saya seperti bentuk wayang yang disajikan
sebagai ilustrasi dalam buku ini. Sudah pasti dimulai dengan yang sangat
sederhana dalam bahan maupun bentuknya, kemudian mengalami perubahan secara
relatif pelan menjadi bentuk wayang yang disajikan dalam buku ini.
Dalam
buku ini tidak dibahas tentang sejarah terjadinya dan perkembangan wayang dari
awal mula hingga yang ada sekarang. Demikian juga tentunya ada wayang-wayang
yang dibuat setelah bentuk wayang yang disajikan di sini. Oleh karena itu bila
para pembaca ada yang berpendapat bahwa wayang-wayang yang disajikan sebagai
ilustrasi buku ini tergolong wayang-wayang lama, tentunya pendapat yang
demikian juga tidak salah. Walaupun sebenarnya wayang-wayang zaman Kartasura,
Mataram, Pajang, dst, dibuat sebelum wayang-wayang ini. Karena sebagai contoh,
dari segi bentuk muncullah "Wayang Ukur" yang diciptakan oleh Sigit
Sukasman pada tahun 1974 di Yogyakarta, saya pernah melihat dan mengamati di
Museum Wayang SENAWANGI Jakarta Kota. Adanya wayang Madya, wayang Wahyu, wayang
Sadat, wayang Suluh, wayang Kancil, wayang Pancasila, dan mungkin masih ada
yang lain lagi, semua ini dibuat pada masa setelah wayang purwa gaya Surakarta
ini ada. Demikian juga saya pernah melihat dan mengamati wayang kulit gaya Surakarta,
tetapi ornamen dalamnya telah ditatah dan disungging secara lebih lembut/halus
tidak seperti ornamen wayang-wayang yang disajikan sebagai ilustrasi buku ini.
Wayang yang demikian itu pernah saya lihat dan amati pada wayang koleksi Prof.
DR. Soedjarwo mantan menteri kehutanan. Wayang tersebut sering dipergunakan pada pergelaran yang sering diadakan di
Jakarta. Berdasarkan bahan yang dipergunakan,
wayang ini adalah wayang kulit, karena dibuat dari kulit kerbau yang
dikeringkan, dikupas/dikerok bulunya, dipotong-potong, ditatah/dipahat dan
disungging/diwarnai. Karena selain kulit kerbau ada wayang yang dibuat dari
bahan kayu, misalnya: wayang krucil, wayang gedog, wayang purwa kayu, wayang
golek cupak, wayang golek pasundan dan sebagainya. Wayang yang dibuat dari kain
disebut wayang beber. Di samping ada wayang yang dibuat dari daun tal, yang
merupakan permulaan wayang dibuat orang, demikian menurut R.M.Sayid. Menurut
kisah yang dikelirkan, wayang-wayang dalam buku ini adalah wayang purwa, yaitu
wayang yang dipergunakan untuk memperkelirkan cerita-cerita dalam Serat Pustakaraja Purwa, Ramayana dan Mahabarata. Karena selain wayang Purwa
ada juga wayang Gedog dan wayang Madya. Wayang Gedog dipergunakan untuk
memperkelirkan cerita Panji. Sedangkan Wayang Madya dipergunakan untuk memperkelirkan cerita setelah wayang purwa,
cerita setelah selesai perang Baratayuda, dari Prabu Parikesit hingga Prabu
Jayabaya di Penjalu/Jenggala. Sehingga cerita dalam wayang madya merupakan
sambungan dari wayang purwa, cerita dalam wayang gedog merupakan sambungan dari
wayang madya. Di samping adanya wayang Menak, wayang Sadat, wayang Pancasila,
wayang Potehi, wayang Suluh, wayang Wahyu, wayang Kancil dan sebagainya yang
memang tidak ada hubungan cerita dengan wayang Purwa ini. Gaya atau gagragnya
adalah Surakarta, karena ada wayang kulit purwa gaya Yogyakarta, Banyumasan,
Pesisiran, Cirebonan, Betawi, Jawa Timuran, Bali, Sasak, Palembang, Banjar dan
sebagainya. Oleh karena itu, isi buku ini masih membatasi diri hanya dalam
lingkup Wayang Kulit Purwa Gaya
Surakarta.
Pertunjukan wayang sampai saat sekarang masih tetap
mendarah daging, tetap digemari dan dihayati serta dijunjung tinggi oleh masyarakat, karena pertunjukan
wayang itu berisi hal-hal yang masih diperlukan dalam kehidupan manusia. Baik
dalam lapangan keduniaan (lahiriah) maupun dalam lapangan mental (bathiniah).
Demikian menurut Ir. Sri Mulyono. Walaupun pendapat ini sebenarnya
kontroversial, namun rasanya saya cenderung terpengaruh oleh pendapat Ir. Sri
Mulyono tersebut di atas. Kalaupun dewasa ini ternyata sudah jarang ada
pergelaran wayang kulit, kalaupun ada penonton atau penggemarnya sudah jarang.
Hal ini sebenarnya tidak disebabkan oleh karena wayang sudah tidak digemari
masyarakat lagi, tetapi hal ini disebabkan adanya perubahan, perkembangan
pengetahuan dan kualitas masyarakat itu sendiri, sehingga pementasan pergelaran
wayang kulit pun dituntut harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat tadi.
Penonton atau penggemar wayang pada zaman Majapahit tentunya pandangan hidupnya,
keadaannya, kualitasnya berbeda dengan penonton atau penggemar wayang pada zaman Sultan Agung di Mataram. Apalagi
jika dibandingkan dengan penonton atau penggemar wayang pada zaman globalisasi
informasi sekarang ini. Karena menurut pengamatan saya, pergelaran wayang yang
disesuaikan sarana dan tehnik pergelarannya yang meliputi sistem cahaya dan
suara, jumlah wayang yang lengkap dengan kelir dan gawangan yang cukup
artistik, simpingan wayang yang cukup panjang, gamelan lengkap pelog sledro
ditambah bedug tambur terompet dan mungkin instrumen musik lainnya, para nayaga
dan pesiden yang terampil menguasai segala gending dan mungkin lagu-lagu
populer, pergelaran dibawakan oleh Dalang yang kaya akan sanggit dan
kreatifitas, aspiratif dan komunikatif dengan penonton, terampil dalam sabetan
(menggerakkan wayang), ternyata masih membanjir juga penonton atau
penggemarnya. Baik pergelaran itu diadakan di desa-desa maupun di kota-kota,
bahkan di ibu kota Jakarta sekalipun. Menurut pengakuan Ki H.Anom Suroto Lebdo Carito
dalam kaset rekamannya, di luar Jawa pun banyak yang menonton sampai pergelaran
selesai, walaupun mereka mungkin tidak mengerti bahasa Jawa.
Karena dalam pertumbuhannya, fungsi
wayang juga telah mengalami perubahan. Sejak dari fungsi sebagai alat suatu
upacara yang ada hubungannya dengan kepercayaan (magis religius) hingga menjadi
alat pendidikan yang bersifat didaktis dan sebagai alat penerangan lalu menjadi
bentuk kesenian daerah dan kemudian menjadi obyek ilmiah, demikian menurut Ir.
Sri Mulyono. Walaupun dalam pekan wayang Indonesia ke VI tahun 1993 di Jakarta
ada juga pakar yang berpendapat bahwa wayang hanya berhenti sebagai tontonan
saja. Namun demikian saya tetap berkeinginan untuk menunjukkan bentuk-bentuk
tokoh wayang yang saya miliki, yang mungkin paling tidak dapat mengisi sesuatu
yang diperlukan oleh masyarakat pewayangan.
Walaupun banyak buku tentang wayang yang
mengungkapkan filsafatnya, ceritanya,
sejarahnya, seni pedalangannya maupun seni kriyanya, namun masih sedikit yang
menyajikan foto wayang dengan corekan/sket/pola yang dibuat oleh penulisnya
sendiri, khususnya wayang kulit purwa gaya Surakarta ini. Di samping saya
merasa terpengaruh oleh optimisme Ir. Sri Mulyono bahwa wayang akan menjadi
milik jagad hingga orang semesta buana akan mempelajari dan mendalami wayang.
Dengan terselenggarakannya festival gamelan Internasional pada tanggal 29
Desember 1995 di taman wisata candi Prambanan Yogyakarta, kiranya tidak
mustahil fenomena yang sama terjadi pada wayang. Ternyata pada tahun 2003 badan
dunia PBB melalui UNESCO telah memberikan penghargaan kepada Wayang Indonesia
sebagai a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of humanity
atau Warisan Budaya Dunia yang luar biasa.
Dari inspirasi inilah timbul keberanian saya dengan segala
keterbatasan saya menyajikan buku ini yang merupakan kumpulan dari apa yang
pernah saya gemari, amati dan pelajari dari sumber-sumber terkait sedari saya
masih anak-anak, walaupun penelitian dan pengamatan langsung pada wayang-wayang
pusaka keraton Mangkunegaran belum pernah saya lakukan. Oleh karena itu saya
sadar bahwa pengetahuan di bidang wayang kulit gaya Surakarta ini masih belum
memadai dibandingkan dengan luasnya pengetahuan wayang kulit yang sebenarnya,
khususnya wayang kulit purwa gaya Surakarta ini. Untuk itu apa yang disajikan
di sini, hanyalah merupakan kesan pribadi saya.
Wayang satu kotak sebenarnya cukup sebanyak lebih kurang
200 saja, tetapi karena adanya wanda wayang yang lebih dari satu, semua tokoh
dibuat sehingga boleh dikatakan tanpa ada tokoh wayang yang dipinjamkan atau
digantikan tokoh wayang lain, maka jumlah tersebut dapat lipat dua kali atau
lebih. Apalagi bila tokoh wayang Korawa seratus benar-benar dibuat, hal
tersebut pernah dinyatakan oleh Ki Manteb Sudharsono dalam pergelaran di museum
Purnabakti TMII. Menurut R.M.Sayit, jumlah wayang Sebet ciptaan Mangkunegara IV, 418 buah.
Walaupun dalam suatu pergelaran yang disediakan seperangkat wayang yang
lengkap, baik tokoh-tokoh wayangnya maupun wandanya, namun masih jarang seorang
Dalang mengeluarkan wayang dengan tokoh yang sebenarnya, apalagi wanda wayang
yang memang cocok dan sesuai dengan kondisi atau suasana jalannya cerita. Yang
saya maksudkan di sini adalah seumpamanya tokoh wayang Batara Bayu ada
janganlah digantikan dengan Tuguwasesa. Seumpamanya tokoh wayang Prabu Parikesit, Sasikirana, Suryakaca,
Jayasumpena, Janurwenda, Sangasanga, Dwara, Arjunapati, Suwarka, disediakan,
janganlah digantikan dengan tokoh wayang baku semacam Prabu Rama Wijaya, Gatotkaca, Antareja, Antasena, Setyaki, Gunawan
Wibisana, Bomanarakasura dan sebagainya. Janganlah menggunakan wayang baku
untuk menggantikan tokoh-tokoh lain. Jangan menggunakan Denawa Patih untuk
tokoh Rukmuka dan Rukmakala dalam lakon ”Dewa Ruci” atau Ditya Wilkataksini
dalam lakon ”Anoman Duta”. Penggantian yang demikian dapat menimbulkan
kekecewaan pada penonton wayang yang benar-benar memahami wayang, di samping
menimbulkan kekeliruan pemahaman bagi penonton wayang yang benar-benar atau
kurang memahami wayang. Karena kekhawatiran inilah mungkin dapat meningkatkan
motivasi kepada diri saya untuk membuat wayang secara lengkap. Namun
keterbatasan dana, waktu, kesempatan dan besarnya/prosentase tanggung jawab
saya terhadap dunia pewayangan sangat menentukan hasil karya saya. Semestinya
keinginan yang demikian akan lebih berhasil apabila dilakukan oleh para Dalang
yang dekat di hati pencinta wayang dan pembuat wayang yang memiliki cukup dana,
serta pemerintah yang tidak kalah pentingnya dalam peran memberikan dorongan dan
pembinaan maupun pemberian subsidi kepada para penatah dan penyungging wayang di
seluruh Indonesia. Begitu juga dalam suasana sedih, gembira, ragu, kaget,
marah, tua, muda, dan lainnya, tentunya tokoh wayang yang dikeluarkan
seharusnya berbeda walaupun namanya satu. Inilah sebenarnya kegunaan dari pada
dibuatnya bermacam-macam wanda. Namun karena para Dalang mungkin cenderung
mementingkan kriteria "cepengan" (bahasa Jawa), artinya
enak dipegang/digerakkan dan mungkin wayang-wayang tersebut milik
pribadi Dalang. Maka perihal pengeluaran tokoh wayang yang benar dalam arti
nama maupun wanda masih banyak diabaikan oleh para Dalang.
Dalam seperangkat satu kotak wayang, menurut letak di
pakeliran dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu "wayang
simpingan" dan "wayang dudahan". Wayang
simpingan disebut juga wayang sumpingan atau wayang panggungan, artinya wayang
yang pada waktu pakeliran diletakkan berjejer pada geber (kelir) ditancap tegak
pada batang pisang di sebelah kiri dan kanan Ki Dalang. Sedangkan wayang dudahan
adalah wayang yang pada waktu pakeliran diletakkan tetap di dalam kotak di
sebelah kiri dan eblek di sebelah kanan Ki Dalang.
Wayang simpingan dibagi menjadi dua yaitu "simpingan
kiri" dan "simpingan
kanan". Wayang-wayang simpingan sebelah kiri banyak didominasi
wayang-wayang yang bermuka disungging warna merah. Berbeda dengan wayang-wayang
simpingan kanan yang banyak didominasi muka warna hitam. Pada simpingan kiri
banyak wayang yang bermulut prengesan atau gusen, gusen bertaring, wayang yang
bermulut ngablak/terbuka/menganga nampak
gigi-gigi dan taringnya. Sedangkan di simpingan kanan tidak terdapat bentuk
mulut yang demikian, sebagian besar "keketan". Demikian juga wayang
simpingan kiri banyak bermata jenis "plelengan", "kedelen",
walaupun ada juga yang bermata
"liyepan"/"gabahan"/"jahitan", sama dengan
simpingan kanan. Lebih khusus lagi di simpingan kanan banyak wayang bermata
"telengan", artinya bentuk mata bulat seperti "plelengan",
tetapi tidak nampak kelopak matanya. Jenis kelamin laki-laki semua, kecuali
Batari Durga, sedangkan beberapa wayang putren (wanita) hanya disimping di
sebelah kanan. Wayang simpingan kiri banyak yang berhidung bentuk "nyantik
palwa"/"haluan perahu", "mungkal gerang" atau
"dempak", sedangkan di simpingan kanan banyak yang berhidung mancung.
Dari sudut karakteristik wayang-wayang yang disimping di sebelah kiri banyak
menunjukkan watak angkara murka, beringas, mudah marah, kurang tahu akan
nilai-nilai kebaikan, tidak segan melanggar nilai-nilai kebaikan, kurang
bertanggung jawab, suka berbalas dendam dan sebagainya. Berbeda dengan
wayang-wayang yang disimping di sebelah kanan banyak menunjukkan tokoh berwatak
berbudi luhur, bijaksana, sabar, bertanggung jawab, sentosa mawas diri, tenang dan
sebagainya. Oleh karena beberapa perbedaan tersebut di ataslah, maka tidak aneh
bila ada beberapa pakar yang menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam
pewayangan yang sudah mapan adalah sangat harmoni, sangat hitam putih, sangat
mengkutub. Oleh karena pengelolaan konflik berdasarkan harmoni hanya memadai
dalam kondisi sosial yang ditandai oleh keadilan dan stabilitas. Tetapi tatanan
stabil tradisional yang adil itu tidak ada lagi. Karena itu identifikasi
pewayangan dengan kedok harmoni perlu dibuka. Keberanian, kemandirian dan tanggung
jawab pribadi yang berorientasi pada kejujuran dan keadilan adalah sikap yang
dituntut sekarang. Sehingga dengan demikian apakah nilai-nilai harmoni
pewayangan perlu ditinggalkan dan tidak perlu dilestarikan lagi. Namun perlu
juga ditunjukkan di sini, bahwa masih banyak pula para pakar yang menyatakan
dalam kebenaran hakiki selalu terkandung sisi baik di balik sisi jahat para
tokoh. Tidak ada salahnya belajar melihat sisi baik di balik sisi jahat. Saya
sendiri memiliki keyakinan bahwa timbulnya yang abu-abu itu berkat adanya yang
hitam dan putih tentunya. Memang dalam etika wayang yang sudah mapan, tentunya
masih kita jumpai: "sapa sing tumemen bakal ketemu", "ngunduh
wohing pakarti", "sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti",
"tan hana dharma mangrawa" dan sebagainya. Walaupun dalam kehidupan
nyata, kadang-kadang masih dijumpai nilai-nilai pewayangan dimanfaatkan sebagai
alat untuk mempertahankan dan memperkokoh status quo, sekedar untuk alat orasi
dan retorika, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan yang
berslogan kebaikan, kedurhakaan berselubung kesalehan, kezaliman berkedok
kebijakan, kecurangan berdalih kejujuran, penindasan bertopeng belas kasihan,
namun kebenaran hakiki tetap ada. Cepat atau lambat kejahatan tetap kejahatan, kebaikan
tetap kebaikan. Kecurangan dapat disulap menjadi kejujuran sementara, namun
tidak akan dapat disulap menjadi kejujuran selama-lamanya. Dalam kehidupan
nyata, khususnya dalam tatanan masyarakat yang belum adil dan setengah modern
atau mungkin modern, demi memperoleh suatu keuntungan tertentu, seseorang dapat
menyamar atau mengidentitaskan dirinya sebagai Pandawa yang berbudi luhur,
mawas diri, bijaksana, selalu ingin memelihara ketenteraman dunia, tidak
mengumbar segala hawa nafsu, membela dan melindungi kaum lemah dan sebagainya.
Oleh karena itu bukan berarti nilai-nilai pewayangan yang harus dibuka dan
dibongkar. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana identitas Pandawa tersebut jangan
sampai digunakan oleh Korawa. Atau paling tidak penyamaran tersebut cepat
terbongkar, cepat diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga kiranya kurang tepat
bila nilai-nilai pewayangan divonis terlampau hitam-putih, sangat harmoni atau
sangat mengkutup. Yang jelas semua ini tergantung bagaimana konteks yang ada.
Memang dalam cerita-cerita Ramayana mungkin masih banyak nampak nilai-nilai
hitam putihnya, namun dalam Mahabarata banyak sekali kebimbangan, keraguan,
keabu-abuan (bukan hitam bukan putih). Kebimbangan nilai-nilai tersebut
tercermin dalam kisah tokoh-tokoh seperti Kumbakarna, Gunawan Wibisana, Adipati
Karna, Puntadewa dalam permainan dadu dan sebagainya.
Sebenarnya saya bukan bermaksud menguraikan wayang kulit
purwa gaya Surakarta ini dengan pendekatan filsafati, khususnya filsafat
tingkah laku atau etika, di mana penuh dengan sisi kontroversial, apalagi bila
diulas oleh seorang yang berada di luar kehidupan penghayatan budaya wayang
yang Jawais, mereka hanya sekedar sebagai pengamat peneliti etika wayang. Dalam
hal ini bukan berarti saya tidak menyukai inovasi dan berniat mengecilkan
peranan para pakar tersebut. Namun karena saya lahir dibesarkan dan dipengaruhi
oleh masyarakat yang berkebudayaan Jawa agraris, kiranya sangat sadar
sedalam-dalamnya bahwa dalam sanubari saya mengalir dengan pekat dan deras
nilai-nilai "tan hana dharma mangrawa", "wong cidra mangsa
langgenga", "sing becik ketitik sing ala ketara", "ngundhuh
wohing pakarti". Sehingga kelicikan Patih Sengkuni untuk memenangkan
Korawa tentunya tidak sama dengan kearifan dan kebijakan Prabu Kresna untuk
memenangkan Pandawa. Saya pandang sangat berbahaya sekali apabila Patih
Sengkuni dan Prabu Kresna, Korawa dan Pandawa, Rahwana dan Arjuna Sasrabahu
atau Rama Wijaya kemudian bergeser menjadi dua kutub yang tidak antagonis.
Kalau pendapat yang demikian terjadi sebenarnya hanya salah pemahaman bagi para
pakar pengamat etika wayang. Apalagi jika obyek-obyek pengamatannya mungkin
kurang akurat dikarenakan pengamatan pada pergelaran dengan Dalang yang kurang
tepat dalam sanggit, sehingga bisa saja terjadi pengubahan atau penggeseran
patokan baku nilai moral. Karena ketatnya persaingan, banyak para Dalang yang
ingin tampil beda sengaja mengubah karakter tokoh tertentu sehingga terlalu
jauh menyimpang dari patokan baku moral wayang. Tokoh-tokoh Pandawa dibuat
berseloroh seperti dagelan atau punakawan, hanya sekedar untuk tampil beda
dengan Dalang-Dalang lainnya, hanya sekedar untuk memperoleh kepopuleran
pribadi pionir perubahan, bukankah tokoh Pandawa ini harus kita tempatkan untuk
melambangkan kejujuran, budi-luhur, bijaksana, membela yang tertindas, hidup
sederhana dan sebagainya. Tokoh Batara Kresna ditempatkan sebagai orang yang
tidak bersih, sebagai tokoh yang disudutkan karena kesalahannya. Bukankah ini
dapat menyinggung kelompok masyarakat yang meyakini bahwa Mahabarata merupakan
tunutunan hidupnya. Kiranya ada benarnya apa yang dikatakan oleh seorang Dalang
dalam rekamannya, bahwa wayang dapat diibaratkan sebagai kawat sampiran (kawat
gantungan). Sehingga dalam pakeliran akan digantungi apa pun bisa, akan
dibebani pesan apa pun boleh, akan dimasuki misi apapun bisa, tergantung pada
kesanggupan dan kemahiran Ki Dalang tentunya. Dengan semakin kontroversialnya,
semakin beragamnya pendapat para pakar, sanubari saya lebih tergugah untuk
melengkapi, menambahkan kepustakaan wayang dalam bentuk kumpulan wayang-wayang
simpingan kiri, kanan dan dudahan ini. Karena analisa dengan pendekatan
filsafat bukan bidang saya, apa pun pendapat para pakar adalah sesuatu yang
saya anggap wajar, efektif atau tidaknya wayang sebagai sarana pendidikan budi
pekerti, perlu atau tidaknya orientasi wayang dibongkar kiranya masyarakat
beserta para pakar dan tokoh pewayangan sendirilah yang dapat menjawabnya.
Anggaplah semua ini merupakan suatu tantangan bagi masyarakat pewayangan yang
perlu segera dijawab dalam arti bebas dari sektarianisme, bila mungkin dalam
arti universal. Namun ada pakar yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat dalam
pewayangan memang harus ada, jadi tidak perlu harus sama. Sebab pengamatan
antar individu bersifat subyektif relatif, tergantung kemampuan, pengalaman,
ketajaman penalaran dan intuisi seseorang. Karena saya mungkin hanya kelompok
kaum mapan yang menjunjung tinggi seni budaya wayang sebagai seni budaya yang
adi luhung. Oleh karena itu saya sadar sedalam-dalamnya bahwa pembahasan atau
analisa masalah "nilai" (termasuk di dalamnya nilai-nilai pewayangan)
sangat berbeda dengan "fakta". Karena "fakta" berbentuk
kenyataan (konkrit), sehingga keberadaannya dapat diuji, karena fakta dapat
ditangkap oleh panca-indera. Sedangkan "nilai" (khususnya nilai-nilai
pewayangan) berbentuk "ide" (abstrak), sehingga eksistensinya tidak
mungkin diuji baik dan buruknya, betul dan salahnya. Melainkan hanya dapat
dihayati. Sedangkan penghayatan atas
sesuatu hanya dapat dicapai dengan cara merenungkan sesuatu itu
sedalam-dalamnya melalui pertimbangan. Yang jelas apabila nilai-nilai
pewayangan masih dapat digunakan sebagai landasan etika moral, tentunya kita
dapat menanyakan pada diri masing-masing, apakah yang kita perbuat di dunia
selama ini sebagai Rahwana, Sengkuni, Durna, Korawa atau Gunawan Wibisana,
Adipati Karna, Kumbakarna, Bambang Sumantri atau Arjuna Sasrabahu, Rama Wijaya,
Kresna, Yudistira atau campuran di antara tokoh-tokoh tersebut.
Dalam buku ini sistematika penyajiannya dimulai dari
wayang dengan ukuran paling tinggi/paling kiri atau paling kanan ke arah yang
paling kecil. Karena dalam pakeliran simpingan diatur demikian rupa berurutan
dari wayang yang berukuran besar tinggi ke dalam ke arah wayang yang terkecil.
Hal ini dilakukan untuk memperoleh keindahan, simpingan yang tidak berurutan
tinggi rendahnya ukuran wayang disebut bejujag (bahasa Jawa). Demikian
sistematika penyajian untuk wayang-wayang simpingan. Untuk wayang-wayang
dudahan akan disajikan secara kelompok demi kelompok, tanpa pertimbangan tinggi
rendahnya dan besar kecilnya wayang. Karena saat pakeliran wayang-wayang
dudahan tetap berada dalam kotak, tidak terlihat oleh penonton, kecuali Ki
Dalang menghendaki demi jejeran/adegan tertentu.
Telah beberapa kali saya sebutkan di atas alasan-alasan
penulisan buku ini, namun secara eksplisit diharapkan buku ini bermanfaat bagi
para peminat, khususnya bagi mereka yang mengetahui cerita wayang, tetapi belum
tahu bentuk dari wayangnya atau mungkin sebaliknya. Di samping dapat mengisi
sela-sela kebutuhan masyarakat pewayangan, mungkin dapat merangsang timbulnya
kreasi-kreasi baru dalam seni kriya wayang. Kalaupun tidak dikatakan
berlebihan, mudah-mudahan buku ini dapat juga membantu melestarikan dalam bentuk
dokumentasi seni budaya wayang kulit purwa yang pernah ada di bumi Nusantara
ini, khususnya wayang kulit purwa gaya Surakarta. Memang banyak cara untuk
mempelajari wayang, namun menurut hemat saya untuk lebih cepat memahami dengan
waktu lebih singkat, biaya relatif ringan, di antaranya masyarakat dapat
mempelajari dalam bentuk tulisan atau buku semacam ini. Istilah-istilah yang
dipergunakan dalam buku ini, khususnya rincian bagian dalam wayang banyak
mengutip istilah-istilah dari buku-buku tentang seni kriya (tatah sungging)
wayang. Oleh karena itu bagi pembaca yang benar-benar awam dalam peristilahan
tersebut, saya anjurkan membaca buku-buku tentang seni kriya (tatah sungging)
wayang. Karena dalam buku ini diusahakan untuk tidak terlampau banyak mengulang
dan mengutip sesuatu yang pernah disajikan dalam buku-buku lain, maka dengan
sengaja tidak dijelaskan di sini. Istilah-istilah yang saya maksudkan antara
lain: rincian dari bagian-bagian wayang, jenis dan bentuk hidung, mulut, mata,
kepala, tangan, badan, kaki, pakaian dan sebagainya.
Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan sebagai
pendahuluan, guna memandu pembaca, sehingga saya harapkan pembaca dapat dengan
mudah memahami isi buku ini.
Simpingan Kiri
1.
BRAHALA.
Gambar-1: BRAHALA MAKUTAN
Gambar-2:
BRAHALA RAMBUT TERURAI
Wayang ini dikeluarkan saat sang tokoh sedang
triwikrama karena telah habis kesabaran dan kebijaksanaannya sehingga nafsu
amarahnya memuncak. Disebut juga Brahalasewu atau Balasewu. Tokoh-tokoh yang
dapat bertriwikrama menjadi Brahalasewu adalah Batara Guru, Batara Ismaya,
Batara Wisnu, Prabu Arjuna Sasrabahu, Prabu Kresna, Prabu Darmakusuma dan
mungkin masih ada yang lain lagi.
Batara Guru dan Batara Ismaya bertriwikrama
terjadi dalam lakon carangan seperti lakon Kresna Boyong, Pandawa Maneges dsb,
dapat didengarkan dalam kaset rekaman wayang yang dibawakan oleh seorang Dalang
yang sudah cukup terkenal.
Semua wayang yang menjadi titisan Batara
Wisnu dapat bertriwikrama, sebagai contoh: Prabu Arjuna Sasrabahu saat
berperang menghadapi Bambang Sumantri dalam lakon Sumantri ngenger atau Prabu
Arjuna Sasrabahu saat membendung muara sungai Gangga dalam lakon Arjuna Sasra
Cangkrama Samudra. Prabu Kresna dalam lakon Kresna Gugah dan Kresna Duta.
Demikian juga Prabu Darmakusuma raja Amarta, apabila dalam keadaan terdesak,
kesabaran dan kebijaksanaan tidak mampu lagi untuk menyelesaikan pertikaian
maka bertriwikramalah menjadi raksasa yang besar sekali dan mengerikan yang
disebut Brahalasewu. Namun dalam buku
ini ditunjukkan dua jenis Brahala masing-masing dua wayang. Jenis pertama
Brahala yang berwujud Buta Raton dengan ukuran lebih besar disungging warna
putih dan berwujud raksasa berambut terurai/gimbal (bahasa Jawa) disungging
warna emas/prada untuk Brahala Darmakusuma yang terkenal berdarah putih. Yang
kedua Brahala yang berwujud Buta Raton berukuran besar disungging warna hitam
dan berwujud raksasa berambut terurai/gimbal muka disungging warna merah.
Karena dalam suatu lakon ada kemungkinan harus mengeluarkan dua Brahala, yang
satu Brahala Prabu Kresna, dan yang satu Brahala Prabu Darmakusuma yang datang
bersama-sama kekayangan Suralaya menghadap Batara Guru untuk menuntut keadilan,
maka di sini disajikan dua jenis Brahala. Namun untuk simpingan kiri
ditunjukkan Brahala Buta Raton ukuran besar yang disungging warna putih dan
Brahala raksasa rambut gimbal dengan badan disungging warna emas/prada, muka
disungging warna merah. Selainnya akan disajikan dalam simpingan kanan, karena
warna sunggingan hitam dan gemblengan/prada.
2. BUTA RATON.
Gambar-3: BUTA RATON MUKA DISUNGGING WARNA MERAH
Gambar-4: BUTA RATON MUKA DISUNGGING WARNA PRADA (EMAS)
Gambar-5: BUTA
RATON MATA MORGAN
Gambar-6: BUTA RATON MATA KELIPAN
Buta Raton
artinya Raksasa Raja. Wayang ini dalam pakeliran mempunyai banyak sekali nama.
biasanya menggambarkan seorang raja yang berwujud raksasa, berwatak
angkaramurka, oleh karena itu muka disungging warna merah. Kecuali untuk tokoh
Kumbakarna biasanya muka disungging warna prada, namun jika wayang yang
demikian tidak tersedia digunakan juga Buta Raton yang mukanya disungging warna
merah, atau semua ini tergantung pada selera Ki Dalang. Karena tujuan pokoknya
untuk menunjukkan bahwa Raden Kumbakarna ini walaupun berwujud raksasa besar,
masih berwatak ksatria. Terkenal dalam serat Tripama karya Sri Mangkunegara IV.
Karena Raden Kumbakarna berperang melawan bala tentara Sri Rama bukan untuk
membela kakaknya Prabu Rahwana, tetapi dia berperang hanya untuk membela tumpah
darahnya atau tanah airnya. Karena Raden Kumbakarna tahu bahwa pihak kakaknya
prabu Rahwana yang salah, sedangkan Sri Rama yang titisan Batara Wisnu berada
dipihak yang benar. Nama-nama Buta
Raton yang sering disebutkan dalam pakeliran antara lain:
PRABU KALA
TREMBOKO.
Prabu Kala
Tremboko dalam Ensiklopedi disebut juga Prabu Arimbaka. Ia adalah seorang raja
raksasa di kerajaan Pringgandani. Permaisurinya bernama Handiba. Putra-putranya
adalah: Arimba, Dewi Arimbi, Arya Prabakesa, Brajadenta, Brajamusti,
Brajalamadan, Brajawikalpa dan Kala Bendana. Menurut Ki Narto Sabdho masih ada
putra dari selir yang bernama Haribawana yang berupa raksasa juga. Prabu Kala
Tremboko menang dalam peperangan melawan Prabu Bomantara raja negara Prajatisa,
sehingga negara tersebut menjadi taklukannya dan tampuk pimpinan negara
diserahkan kepada Prabu Narakasura penggantinya.
Prabu Kala
Tremboko binasa dalam peperangan menggempur negara Astina melawan Prabu
Pandudewanata dalam lakon perang Pamuksa. Prabu Kala Tremboko melawan Prabu
Pandudewanata karena ingin mati di tangan manusia yang tahu sastrajendrahayuningrat,
sehingga beliau dapat mati sempurna.
PRABU GORAWANGSA.
Prabu Gorawangsa
adalah raja negeri Bombawirayung. Dia dapat berubah rupa menjadi Prabu Basudewa
raja Mandura, karena diketahui Prabu Basudewa sedang berburu ke hutan, sehingga
dapat bermain asmara dengan Dewi Maherah permaisuri Prabu Basudewa.
Karena bantuan
Prabu Pandudewanata, Prabu Gorawangsa dapat dibinasakan. Hasil permainan
asmaranya dengan Dewi Maherah melahirkan Raden Jaka Maruta atau Kangsa Dewa
yang kemudian menuntut ingin diangkat menjadi putra mahkota negara Mandura.
Bentuk wayangnya juga salah satu dari beberapa wayang Buta Raton ini.
PRABU BAKA.
Prabu Baka adalah
raja negeri Ekacakra. Ia suka memakan orang. Rakyatnya secara bergilir
diwajibkan memberi upeti berupa orang seorang ditambah nasi segerobak. Prabu
Baka binasa oleh Raden Bratasena pada saat Para Pandawa tinggal dinegara
Ekacakra setelah lakon Bale Sigalagala, menumpang pada seorang Brahmana yang
bernama Resi Japa. Karena Resi Japa sekeluarga mendapatkan giliran untuk
memberikan upeti manusia dan nasi segerobak, maka resahlah keluarganya sehingga
istrinya menangis. Karena tangisnya didengar oleh Dewi Kunti, maka ditolonglah
Resi Japa dan keluarganya. Akhirnya Raden Bratasenalah yang akan menjadi ganti
keluarga Resi Japa. Esok harinya membawa nasi segerobak ke depan Prabu Baka.
Nasi tadi tidak diberikan Prabu Baka, melainkan dimakan sendiri oleh Raden Bratasena.
Prabu Baka marah sekali, sehingga terjadilah perkelaian yang amat seru. Prabu
Baka mati terbunuh oleh Raden Bratsena, amanlah negara Ekacakra bebas dari
ancaman rajanya. Lakon ini pernah terlihat pada pergelaran wayang di museum
keprajuritan TMII dengan Dalang yang sudah cukup terkenal dengan lakon Bale
Sigalagala. Wayang Buta Raton inilah yang dipergunakan sebagai Prabu Baka.
PRABU DITYA
YUDAKALAKRESNA.
Prabu Ditya
Yudakalakresna adalah raja raksasa negara Dwarawati yang terakhir, karena
penggantinya tidak berwujud raksasa lagi. Dalam kaset rekaman wayang yang
dibawakan oleh seorang Dalang yang sudah cukup kondang dalam lakon Narayana
Krida Brata, diceritakan bahwa Prabu Ditya Yudakalakresna mati oleh jago-jago
Dewa, yaitu Raden Narayana dan Raden Permadi, karena ingin menyerang Kahayangan
Suralaya. Namun pernah terlihat dalam suatu pergelaran tokoh Prabu Ditya
Yudakalakresna digunakan wayang Buta Raton dengan sunggingan warna hitam.
PRABU HARIMBA.
Prabu Harimba
kakak Dewi Arimbi dapat ditafsirkan sebagai Buta Raton dengan mata sipit
besar/kelipan. Prabu Harimba mati terbunuh dan hancur dihantamkan pohon enau
oleh Raden Bratasena pada waktu menyerang Pandawa yang sedang mengembara di hutan
dekat negara Pringgandani yang menjadi kekuasaannya.
PRABU
NIWATAKAWACA.
Prabu
Niwatakawaca adalah raja negeri Imaimantaka atau Manikmantaka. Semula ia tidak
berwujud raksasa, karena pergi bertapa untuk mendapatkan kesaktian agar dapat
mengalahkan Dewa di Suralaya dan dapat mempersunting bidadari Dewi Supraba,
setelah memperoleh kekebalan ia menjadi raja raksasa sangat sakti. Ia tidak
dapat mati bila noktah belang yang berada di langit-langit mulutnya tidak
terkena senjata. Ia kemudian meminang Dewi Supraba menyerang Suralaya, namun
akhirnya dapat dikalahkan dan dibinasakan oleh Begawan Ciptaning Mintaraga atau
Raden Arjuna. Biasanya wayangnya digunakan Buta Raton yang
kedua matanya nampak.
PRABU KALA
PRACONA.
Prabu Kala
Pracona adalah raja raksasa negara Tasikwaja, ada juga yang menceriterakan raja
negara Gilingwesi. Dalam lakon lahirnya Gatotkaca diceritakan bahwa Prabu Kala
Pracona ingin memperistri seorang bidadari Suralaya bernama Dewi Gagarmayang.
Karena lamarannya ditolak, maka ia memerintahkan patihnya bernama Sekipu yang
berwujud raksasa juga untuk menyerang para Dewa di Suralaya. Walaupun Dewa
Suralaya meminta bantuan para Pandawa, namun kekuatan seimbang. Akhirnya Raden
Gatotkacalah yang menjadi jago para Dewa dan dapat membinasakan Patih Sekipu
berserta bala tentaranya, begitu juga Prabu Kala Pracona tewas oleh tangan Raden
Gatotkaca. Wayang yang dipakai sebagai Prabu Kala Pracona biasanya juga Buta
Raton ini. Demikian beberapa contoh dari nama-nama Buta Raton dengan kisah
singkatnya. Adapun mungkin masih banyak lagi nama-nama lain yang sering
disebutkan oleh Ki Dalang dalam pakeliran. Di dalam buku ini telah disajikan
empat Buta Raton dengan satu wayang yang sengaja disungging gemblengan (warna prada seluruhnya) yang
mungkin bisa dipergunakan sebagai tokoh Raden Kumbakarna.
4. BATARA KALA.
Gambar-7: BATARA KALA
Batara Kala
disebut juga Kamasalah. Ia anak Batara Guru yang terjadi dari kama yang jatuh
di tengah Samudra. Pada waktu Batara
Guru bersama permaisurinya Dewi Uma berkeliling jagad tepat di atas Samudra
timbul nafsunya untuk berhubungan layaknya suami istri. Karena Dewi Uma menolak
maka terjatuhlah kama Batara Guru di tengah Samudra, yang menyebabkan
mendidihnya air Samudra disertai suara gemuruh dan menimbulkan hawa panas yang
menggegerkan para Dewa dan Dewi di Kahayangan. Bersamaan dengan keadaan itu
muncullah di tengah-tengah Samudra suatu bentuk/wujud raksasa yang sangat besar
dan mengerikan yang kemudian menyerang para Dewa. Karena para Dewa tidak
sanggup menandingi raksasa tersebut, maka sampailah raksasa itu menghadap
Batara Guru, untuk menanyakan siapa ayahnya. Oleh Batara Guru diaku sebagai
anaknya dengan kedua caling/taringnya dicabut yang kemudian menjadi senjata
Pasopati dan Kunta Wijayacapa. Tentang nama senjata ini banyak versi,
tergantung sanggit Ki Dalang tentunya. Sedangkan rambutnya dicabut
segenggam yang kemudian
menjadi kendeng/tali gendewa yang bermacam-macam. Sedangkan dahinya
ditulisi dengan rajah kala cakra, dinamakan Sastrabinadeti. Atas kehendak
Batara Guru dan persetujuan Batara Narada, Kama Salah diberi nama Batara Kala
dan disuruh mengawini Batari Durga di Kahayangan Setragandamayit atau
Dandangmangore di hutan Krendawahana. Batara Kala tidak dibenarkan memakan
sembarang hewan dan manusia, kecuali manusia yang memiliki sukerta/dosa/nandang
lepating dumadi (bahasa Jawa).
Cerita Batara
Kala ini cukup panjang, khususnya dalam lakon ruwatan atau murwakala.
Pergelaran wayang dengan lakon "ruwatan" atau "murwakala"
merupakan salah satu acara seremonial yang sakral dan diselenggarakan oleh
salah satu atau beberapa keluarga yang dianggap memiliki sukerta. Karena
ragamnya cukup banyak, maka sukerta tersebut tidak mungkin disebutkan dan
dijelaskan secara lengkap, semuanya telah disebutkan secara khusus dalam
buku-buku Ruwatan/Murwakala. Namun secara singkat sukerta tersebut antara lain:
ontang-anting yaitu anak laki-laki satu-satunya, kedana-kedini
yaitu anak dua laki-laki dan perempuan, kembar yaitu anak yang lahir
dalam satu kandungan lebih dari satu, dampit yaitu anak dua lahir dalam
satu hari laki-laki dan perempuan, gondang kasih yaitu dua anak
laki-laki dan perempuan lahir dalam satu hari warna kulitnya yang satu kuning
yang lain hitam, tawang-gantungan yaitu anak kembar atau dampit yang
lahir tidak dalam satu hari, saramba
yaitu anak empat laki-laki semua, bungkus yaitu anak yang lahir
terbungkus ari-ari, wungkul yaitu anak yang lahir tanpa ari-ari, jempina
yaitu anak yang lahir belum waktunya hanya tujuh bulan dalam kandungan, gotong
mayit yaitu anak tiga perempuan semua, dan masih banyak lagi. Tentunya
semua ini hanya gugon tuhon (dalam bahasa Jawa) atau keyakinan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Batara Kala
bermata plelengan, berhidung bentuk haluan perahu, mulut terbuka nampak gigi
dan taringnya, berjamang dengan garuda membelakang, bersurban Dewa, berkain
kerajaan raksasa. Ada juga yang mengelompokkan wayang Batara Kala ini sebagai
wayang dudahan, karena termasuk golongan Dewa. Tetapi dalam pakeliran sering
terlihat wayang ini disimping di simpingan kiri, oleh karena itu disini
dikelompokkan sebagai wayang simpingan kiri.
5. MAHESASURA.
Gambar-8:
MAHESASURA
Mahesasura adalah
raja negara Gua Kiskenda, ia berwujud raksasa yang besar mengerikan berkepala
kerbau dan bertanduk panjang. Patihnya bernama Lembusura berwujud raksasa juga,
tetapi berkepala sapi yang bertanduk panjang. Mahesasura mempunyai saudara yang
dijadikan kendaraan perangnya bernama Jatasura. Jatasura bertubuh banteng
tetapi berkepala raksasa. Prabu Mahesasura berwatak angkaramurka. Istananya
terletak dalam sebuah gua besar yang di dalamnya lebar sekali. Balatentaranya
berwujud raksasa yang tak terbilang jumlahnya, berikut para senopati dan
adipatinya, rata-rata sakti. Kerjanya tiap hari mengganggu rakyat, mereka
merusak tanaman sawah tegalan dsb. Prabu Mahesasura ingin meminang bidadari
Kaindran yang bernama Dewi Tara. Maka diutuslah Patih Lembusura pergi ke
Kahayangan untuk meminta Dewi Tara kepada Batara Indra, untuk dijadikan
permaisuri. Tetapi Batara Indra tidak mengijinkan dan ditolak lamaran
Mahesasura tersebut, sehingga Lembusura pulang ke Gua Kiskenda untuk melaporkan
kejadian itu kepada rajanya. Sebelum bala tentara Prabu Mahesasura menyerang
Kahayangan, diseranglah negara Gua Kiskenda
oleh para Dewa hingga habis binasa bala tentara raksasa Gua Kiskenda termasuk
Patih Lembusura tewas. Tinggal Mahesasura dan Jatasura yang masih hidup bersama-sama
raksasa-raksasa wanita. Para Dewa tidak mampu menandingi perlawanan Mahesasura
dan Jatasura, karena jika yang satu mati, dilangkahi satunya, hidup kembalilah
kedua makluk itu. Namun akhirnya dapat juga dibinasakan oleh jago Dewa yang
bernama Raden Subali, dengan menggunakan sekuat tenaga kedua makluk ajaib, raja
dan tunggangannya itu diadunya sehingga kedua-duanya tewas, darah segar
berwarna merah dan putih mengalir ke sungai keluar gua.
Wayang Mahesasura
ini sebenarnya ada yang berpendapat bukan termasuk wayang simpingan, tetapi
karena selama ini wayang Mahesasura sering terlihat pada pergelaran-pergelaran
selalu disimping, maka di sini dimasukkan dalam wayang simpingan kiri. Bahkan
pada wayang-wayang yang kurang lengkap, tokoh Mahesasura dapat digantikan
dengan wayang Buta Raton.
Wayang Mahesasura
berkepala kerbau nampak tanduknya yang panjang, bermahkota, berpraba, berkain
raja raksasa.
6. PANCATNYANA.
Gambar-9: PATIH PANCATNYANA
Pancatnyana
adalah patih negara Trajutrisna, rajanya bernama Suteja atau Prabu
Bomanarakasura setelah dapat membinasakan Prabu Bomantara. Pada waktu negara
Trajutrisna berperang melawan negara Pringgandani dalam memperebutkan Kikis Tunggarana,
Patih Pancatnyana berhadapan melawan patih Pringgandani yang bernama Prabakesa.
Sedangkan Prabu Bomanarakasura bertanding melawan Raden Gatotkaca.
Patih Pancatnyana
berwujud raksasa besar, berhidung haluan perahu, bermulut menganga nampak
gigi-gigi dan taringnya, bertopong bergaruda
membelakang, berambut terurai, berpraba, tangan belakang irasan, berkain
raja raksasa. Apabila tidak terlengkapi dengan wayang ini, biasanya digunakan
wayang Raksasa Raja Muda atau Buta Patih. Namun pernah terlihat dalam
pergelaran di Surabaya melalui siaran televisi INDOSIAR, seorang Dalang yang
cukup terkenal menunjukkan wayang Patih Pancatnyana dengan wayang tidak seperti
ini, tetapi dengan wayang raksasa rambut terurai, bergaruda membelakang, tangan
belakang terlepas dapat digerakkan, badan disungging warna coklat. Wayang
tersebut mungkin milik pribadi sehingga enak dimainkan di kelir (cepengannya
enak) dan dalam lakon apa pun selalu dikeluarkan di kelir.
7. ANCAKOGRA
Gambar-10: ANCAKOGRA
Nama Ancakogra berasal dari kata ”ancak” yaitu kulit batang pisang atau disebut ”debok” (bahasa Jawa) yang dibentuk empat persegi diberikan ayaman
jarang-jarang bilah bambu di dalamnya yang digunakan tempat menaruh nasi
tumpeng bersama lauknya, sayur mayur dan panggang ayam yang digunakan untuk
sesaji atau selamatan di desa-desa di Pulau Jawa umumnya. Kebiasaan bersih
desa, memohon hujan pada saat kemarau yang berkepanjangan dan lain-lainnya
sering kali dilakukan masyarakat di pedesaan, walaupun mungkin saat sekarang
sudah langka lagi, karena pengaruh agama dan pendidikan yang semakin baik.
Upacara selamatan ini biasanya dilakukan di perempatan jalan dengan
masing-masing anggauta keluarga membawa paling tidak satu ancak, baru kemudian dikumpulkan
ditumpuk menjadi satu di perempatan jalan tempat dilakukan upacara. Setelah
selesai berdoa maka ancak tersebut dibagikan kembali ke anggauta keluarga
sehingga ancak yang diterima kembali akan tertukar dengan ancak warga lain.
Disini terlihat saling tukar menukar ancak yang berisi makanan tersebut. Dalam
upacara ini nampak pula kandungan budaya toleransi keyakinan warga, disebutkan
dalam doa tersebut danyang inkang manggen
wonten keblat sekawan gangsal ingkang dipun lenggahi, Dadungawuk, Dewi Sri dan
Sadana, para Wali para Nabi dan lain sebagainya. Ini adalah hanya sebuah
pengalaman dan kesan pribadi seorang pembuat wayang.
Ancak-ancak tersebut di atas setelah makanannya diambil
dibuang ke tempat sampah. Sehingga dalam dunia pewayangan/pedalangan diceritakan
pada waktu Bambang Suteja dalam perjalanan mencari orang tuanya telah diberikan
ibunya Dewi Pertiwi cangkok kembang Wijayakusuma yang disebut kembang
Wijayamulya. Kembang ini memiliki khasiat dapat menghidupkan benda mati. Di
tengah jalan Bambang Suteja berjumpa dengan seekor burung garuda yang setengah
mati, untuk mencoba kasiat kembang Wijayamulya didekatkan kembang tersebut di
atas burung garuda itu sehingga terbukti burung garuda dapat hidup segar bugar
kembali atau oleh Ki Dalang disebutkan ”jati
waluya temah waluya jati”. Bersamaan dengan kejadian itu ada sesuatu
keanehan, di dekat burung tersebut terkapar sebuah "ancak"
sesaji yang rusak, bangkai burung dara yang sudah busuk dan cadik perahu tua, tempayan
yang rusak, seketika dapat berubah wujud hidup menjadi manusia walaupun
berwujud raksasa. Burung garuda yang sebenarnya bernama Garuda Wilmuna dapat berbicara, akhirnya menjadi kendaraannya.
Demikian juga raksasa Ancakogra yang
berasal dari ancak, Ditya Mahundara yang berasal dari
bangkai burung dara dan Yayahgriwa berasal dari tempayang yang rusak terbuang, Cantekawati yang berasal dari cadik perahu, semuanya mengikuti
perjalanan Bambang Suteja.
Ketika terjadi perselisihan antara Prabu
Sitija/Bomanarakasura dan Prabu Gatotkaca raja Pringgondani, karena perebutan
wilayah Tunggarana, Ancakogra tewas dalam pertempuran melawan Gatotkaca,
dadanya hancur terkena aji Brajamusti. Demikian kisah Ancakogra raksasa jadian
ini.
Wayang Ancakogra apakah seperti ini, tentunya setiap
Dalang, penulis atau pencipta wayang bebas menafsirkannya, mengingat wayang ini
tidak terlampau sering keluar dalam pakeliran. Ini adalah sanggit atau tafsiran
seorang pembuat wayang yang ingin menambahkan jumlah wayang yang sudah ada.
8. KALAKARNA.
Gambar-11: KALAKARNA
Wayang ini
sebenarnya adalah wayang srambahan, wayang yang dapat dipakai sebagai banyak
tokoh wayang lainnya. Selain digunakan sebagai tokoh Kalakarna, dapat juga
digunakan sebagai Patih Prahasta, atau Prabakesa dsb. Ada juga yang menyebutkan
tidak sebagai wayang simpingan, tetapi sebagai wayang dudahan. Namun dalam
pergelaran-pergelaran wayang yang mempergunakan seperangkat wayang yang
lengkap, khususnya pergelaran di Ibukota Jakarta, wayang Kalakarna ini
disimping di kiri. Bila tokoh wayang ini tidak ada, biasanya Patih Kalakarna,
atau Prahasta dapat digantikan wayang Buta Patih. Wayang ini dapat disebutkan
sebagai Patih Kalakarna, Prabakesa, atau Prahasta, karena sering terlihat dalam
buku-buku wayang, sebagai ilustrasinya, ketiga tokoh wayang tersebut sering
ditunjukkan wayang ini. Kisah Kalakarna tersebut dapat dilihat dalam lakon
Alap-alap Surtikanti, Kisah Patih Prahasta diceritakan dalam lakon Lokapala,
Alengka. Kisah Prabakesa dapat dilihat dalam lakon yang menceritakan negara
Pringgandani pada masa Raden Gatotkaca sampai perang Baratayuda.
Wayang Kalakarna
bermata plelengan, berhidung haluan perahu, mulut terbuka nampak gigi-gigi dan
taringnya, bertopong, bergaruda membelakang, berambut terurai, berpraba dan
berkain raja raksasa. Tangan belakang
lepas tidak irasan seperti umumnya wayang raksasa.
9. RAKSASA RAJA MUDA.
Gambar-12: RAKSASA RAJA MUDA ( NAMPAK KEDUA MATANYA)
Gambar-13: RAKSASA RAJA MUDA (NAMPAK KEDUA MATANYA)
Gambar-14: RAKSASA RAJA MUDA
Wayang ini sering
terlihat digunakan sebagai seorang patih raksasa, misalnya Patih Sekipu dari
negara Gilingwesi, Patih Pancatnyana dari negara Trajutrisna, Patih Prahasta
dari negara Alengka, Patih Suratrimantra dari negara Sengkapura, bahkan bila
Patih Lembusura dari negara Gua Kiskenda tidak dilengkapi, dapat juga digunakan
wayang ini. Demikian juga untuk patih-patih dari negara seberang biasa
digunakan wayang ini. Sehingga boleh dikatakan dalam lakon apa pun wayang ini
dapat dikeluarkan dengan nama sekehendah Ki Dalang, khususnya lakon-lakon
carangan.
Dalam
pergelaran-pergelaran memang sering wayang ini ditunjukkan sebagai seorang
patih dari suatu negara tertentu, apalagi jika rajanya juga seorang raksasa
(ditunjukkan dengan Buta Raton). Oleh karena itu kiranya tidak keliru jika
wayang ini ada yang menyebutkan dengan nama Buta Patih. Nama
tersebut pernah terdengar ketika seorang Dalang menyuruh anak-anak yang
menonton di dekat kotak mengambil dari simpingan kiri dengan sebutan Buta Patih.
Sehingga dapat disebutkan juga bahwa wayang ini adalah wayang srambahan. Namun
pernah juga terlihat seorang Dalang yang cukup terkenal menunjukkan wayang ini
dalam lakon ”Sudamala” sebagai Kalantaka dan Kalanjaya, jadi bukan sebagai
patih. Nampaknya kedua wayang tersebut memang milik pribadi atau bawaan Ki
Dalang. Jadi yang jelas wayang ini lebih nampak dikategorikan sebagai wayang
srambahan.
Wayang ini
berhidung bentuk haluan perahu, bermulut terbuka nampak gigi-gigi dan
taringnya, berjamang, bersunting surengpati, bergaruda membelakang, berambut
terurai atau gimbal di punggung dan menutupi seluruh badannya sampai sepanjang
kaki. Tangan belakang irasan, tidak dapat digerakkan, hanya tangan depan yang
lepas dan dapat digerakkan. Di dalam buku ini disajikan tiga wayang, yang satu
morgan nampak satu matanya, berarti miring betul, yang kedua nampak kedua matanya bertopong, sedangkan yang
ketiga nampak kedua matanya garudan, berarti digambarkan agak
miring/metok(bahasa Jawa).
10. JATAGIMBAL
Gambar-15: JATAGIMBAL
Prabu Jatagimbal adalah raja raksasa di negara
Guasiluman. Ia masih keturunan Prabu Kalasasradewa, raja raksasa di negara
Goamiring yang tewas dalam pertempuran melawan Prabu Pandudewanata, karena
bersama prajuritnya menyerang negara Mandura untuk merebut Dewi Arumbini, istri
Arya Prabu Rukma.
Karena ketekunannya bertapa, Prabu Jatagimbal menjadi
sangat sakti, berwatak angkara murka, bengis, dan selalu ingin menangnya
sendiri. Prabu Jatagimbal menikah dengan Dewi Jatagini, dan mempunyai seorang
anak bernama Kalasrenggi.
Untuk membalas dendam kematian ayahnya, Prabu
Kalasasradewa, Prabu Jatagimbal menyerang negara Amarta. Ia ingin membinasakan
keluarga Pandawa yang merupakan keturunan Prabu Pandudewanata. Prabu Jatagimbal
tewas dalam pertempuran melawan Arjuna. Tubuhnya hancur terkena panah Kyai Sarotama.
Dendam keluarga itu rupanya masih berlanjut. Istri
Jatagimbal yang bernama Jatagini memberitahukan anaknya, Kalasrenggi, dengan
berbagai kesaktian untuk membalas kematian ayahnya. Setelah cukup kesaktiannya,
Kalasrenggi pergi mencari Arjuna untuk membalas dendam keluarganya. Dalam
perjalanan mencari Arjuna, ia melihat dari atas seorang ksatria yang tampan dan
dikira Arjuna. Ksatria tampan itu memang anak Arjuna bernama Bambang Irawan
yang dalam perjalanan menuju negara Wirata untuk membantu keluarga Pandawa
dalam perang Baratayuda. Maka dengan cepat Kalasrenggi meniup dari atas dan
langsung menggigit leher Bambang Irawan. Dengan rasa kaget Bambang Irawan
menghunus keris dan dengam cepat menikam dada Kalasrenggi agar melepas
gigitannya. Tetapi Kalasrenggi malahan semakin
kuat menggigit Bambang Irawan, sehingga akhirnya keduanya mati sampyuh (bahasa Jawa). Dalam pewayangan
banyak sekali cerita atau lakon balas dendam ini terjadi, Kalasasradewa adalah
musuh Prabu Pandu, anak Kalasasradewa (Prabu Jatagimbal) membalas kepada
keluarga Pandawa (anak Prabu Pandu), anak Jatagimbal yang bernama Kalasrenggi
membalas dendam kepada keluarga Pandawa dan ketemu Bambang Irawan.
Wayang Jatagimbal ini merupakan tafsiran, karena wayang
ini hanya sekali keluar dan langsung mati, oleh karena itu banyak para Dalang
menunjukkan tokoh Jatagimbal ini dengan wayang berbeda-beda atau wayang
srambahan, dan mungkin wayang miliknya sendiri yang enak dipegang atau enak
untuk sabetan. Prabu Jatagimbal berujud raksasa nampak kedua matanya kelipan,
hidung nyantik palwa, mulut menganga nampak gigi-gigi dan taringnya, berjamang,
rambut terurai di punggung/nggendong, tangan belakang irasan.
11. DITYA KALANJAYA DAN KALANTAKA
Gambar-16: KALANTAKA
Ditya Kalanjaya dan Kalantaka nampak di pakeliran dalam
lakon ”Sudamala”. Dimana kedua raksasa ini sebenarnya Dewa penjaga
Kahayangan Tinjomaya yang sedang menerima pidana berubah rupa menjadi dua
raksasa karena dipersalahkan mengintip Batara Guru yang sedang mandi di sendang
bersama para Bidadari. Kedua raksasa itu sebenarnya bernama Batara Citrasena
dan Citragada. Untuk dapat diruwat pulih kembali mejadi Dewa, kedua raksasa ini
datang ke negara Astina menemui Begawan Durna seorang Pendeta yang sangat
terkenal menguasai segala macam ilmu
pengetahuan. Begawan Durna sanggup meruwat tetapi dengan syarat kedua raksasa
tersebut dapat menyajikan panggang manusia lima bersaudara laki-laki semua.
Lima saudara laki-laki semua adalah para Pandawa, ini merupakan siasat Korawa
untuk menghancurkan Pandawa sebelum perang Baratayuda terjadi.
Dalam perjalanan mencari panggang manusia tersebut, Ditya
Kalanjaya dan Kalantaka bertemu dengan pendeta Parangalas yang bernama Begawan
Tambrapeta dan kedua putrinya Dewi Soka dan Padapa yang sedang mencari Raden
Nakula dan Sadewa. Dilihatnya ada dua wanita yang cantik-cantik, maka kedua
raksasa tersebut mengejarnya. Dalam pengejaran ini mereka berjumpa dengan Raden
Nakula dan Sahdewa, sehingga kedua raksasa ini dapat dikalahkan dengan diadu
dibenturkan kedua kepala mereka hingga tewas. Tewasnya kedua raksasa ini
berubah menjadi Batara Citrasena dan Batara Citragada. Atas jasa meruwat kedua
raksasa ini dan memang kehendak kedua putri tersebut Dewi Soka menjadi istri
Raden Nakula dan Dewi Padapa menjadi istri Raden Sadewa.
Bentuk wayang Ditya Kalanjaya dan Kalantaka mirip Denawa Patih, disini
dibuat kembar nampak kedua matanya, hanya beda di wajah yang satu bersinom
sedangkan yang lain tidak. Jika wayang ini tidak ada dalam satu kotak wayang
yang disediakan bisa saja menggunakan wayang Denawa Patih atau Denawa Prepatan.
Penafsiran ini dilakukan tiada maksud lain
terkecuali ingin menambahkan jumlah wayang yang ada khususnya Gaya
Surakarta ini. Benar dan salahnya terbalik pada para Dalang dan pencinta
wayang.
19. PRABU DASAMUKA.
Gambar-25: DASAMUKA NAMPAK KEDUA MATANYA (BEGAL)
Gambar-26: DASAMUKA (SEMBADA)
Gambar-27: DASAMUKA NAMPAK KEDUA MATANYA (BEGAL)
Gambar-28: DASAMUKA NAMPAK KEDUA MATANYA (BUGIS)
Gambar-29: DASAMUKA TRIWIKRAMA
Dasamuka artinya bermuka sepuluh. Karena kalau triwikrama
kepalanya dapat menjadi sepuluh. Nama aslinya Rahwana, karena pada waktu lahir
berada ditengah hutan dan terdiri dari segumpal darah. Rah berarti darah, wana
berarti hutan. Ibunya bernama Dewi Sukesi, ayahnya bernama Begawan Wisrawa. Prabu
Dasamuka berpermaisuri Dewi Tari. Ia berputra mahkota Indrajit atau Megananda.
Putra-putra dari isteri yang lain diantaranya: Trikaya, Trinetra, Trisirah,
Trimurda, Pratalamaryam dll. Ia naik takhta kerajaan Alengka menggantikan
kakeknya Prabu Sumali, dengan patihnya pamannya sendiri yaitu Prahasta.
Saudara-saudara seayah seibu antara lain: Kumbakarna berwujud raksasa, tinggal
di kesatrian Pangleburgangsa, Dewi Sarpakenaka berwujud raksesi, Gunawan Wibisana
berwajah tampan. Prabu Dasamuka berwatak angkaramurka, ingin menangnya sendiri,
penganiaya dan pengkianat, keras hati, berani serta menuruti kata hatinya
sendiri. Ia sangat sakti, karena mempunyai aji Pancasona yang didapat dari Resi
Subali dan dapat triwikrama menjadi raksasa berkepala sepuluh. Prabu Dasamuka
mengidamkan seorang istri penjelmaan Dewi Widowati. Ia meminang putri negara Ayodya bernama Dewi
Sukasalya, putri Prabu Banaputra. Sesuai
dengan wataknya, ia minta dengan bengis dan mengancam dengan kekerasan,
sehingga mengakibatkan peperangan antara kedua negara itu. Prabu Banaputra
gugur dalam pertempuran. Dewi Sukasalya melarikan diri dari Ayodya untuk
menyembunyikan diri. Resi Baratmadya dan semua yang melindungi pelarian putri
tersebut dibinasakan oleh Rahwana. Akhirnya Resi Dasarata dapat menipunya,
Rahwana diberi Dewi Sukasalya palsu yang segera dibawa kembali ke Alengka,
tetapi Dewi Sukasalya tersebut kembali ke asalnya, menjadi sekuntum bunga.
Rahwana sangat marah, lalu menuntut Resi Dasarata. Resi Dasarata menjawabnya
dengan sebuah kalimat bahwa mati hidup manusia itu ada di tangan Dewa.
Kemarahan Rahwana kemudian beralih ditujukan kepada Dewa dan memerintahkan
angkatan perangnya untuk menggempur Suralaya. Niatnya itu didengar oleh kakaknya
lain ibu yang bernama Prabu Danaraja, raja negara Lokapala. Prabu Danaraja
datang ke negara Alengka untuk memberikan nasehat agar jangan menyerang para
Dewa di Suralaya. Tetapi nasehat itu malahan menjadikan salah paham, sehingga
mengakibatkan terjadinya peperangan antara Rahwana dengan Prabu Danaraja. Prabu
Danaraja akhirnya gugur dalam pertempuran itu.
Pada suatu ketika Rahwana berkelana mencari penjelmaan
Dewi Sri Widowati. Ia melewati di
atas hutan Sunyapringga, di mana Resi Subali sedang bertapa. Karena kesaktian
Resi Subali, Rahwana jatuh dari angkasa. Ia menjadi marah dan menyerang Resi
Subali, sehingga terjadi peperangan antara keduanya. Rahwana kalah dan
menyerahkan diri untuk berguru pada Resi Subali. Aji Pancasona akhirnya
diberikan juga kepada Rahwana. Demikian asal mula Rahwana memiliki aji
Pancasona. Pada zaman Prabu Arjuna Wijaya bertakhta di negeri Maespati, Rahwana
menyerang Maespati dan dapat membunuh Patih Suwandagni/Sumantri. Tetapi ia
dapat ditahan dan disiksa oleh Prabu Arjuna Wijaya/Arjuna Sasrabahu, dengan
diikat serta diseret pada kereta. Sejak itu keangkaramurkaan Rahwana dapat
dipadamkan sehingga dunia diliputi dengan kedamaian. Setelah Prabu Arjuna
Sasrabahu muksa, sifat angkaramurka Rahwana timbul kembali. Karena ia sangat segan
kepada Resi Subali gurunya, maka ia mencari daya upaya untuk membinasakan
gurunya. Dihasut dan diadu dombalah antara Resi Subali dan Sugriwa adiknya,
sehingga timbul perang saudara. Negara Gua Kiskenda dikuasai Resi Subali, Dewi Tara permaisuri Sugriwa
dirampas.
Di dalam Ramayana diceritakan, bahwa Dasamuka berhasil
menculik Dewi Sinta, permaisuri Sri Rama Wijaya. Akibat dari perbuatan ini
terjadi perang besar Alengka, sehingga Prabu Dasamuka gugur oleh tangan Sri
Rama Wijaya dengan perantaraan panah sakti Guwawijaya. Untuk menghindari
kemungkinan bangkitnya kembali Prabu Dasamuka yang telah tewas itu, maka
ditimbunlah oleh Anoman dengan gunung Kendalisada. Konon dalam pedalangan
cerita tentang Rahwana masih ada dalam zaman Mahabarata/Pandawa/Madya, sehingga
rohnya masih berkeliaran yang disebut Prabu Godayitma atau Godakumara,
bertakhta di negara Tawanggantungan atau Suwargabandang. Tetapi semua ini dapat
dikalahkan oleh Anoman yang berumur panjang juga, dan selalu mengabdi kepada
titisan Batara Wisnu yang selalu memelihara ketentraman dunia.
Demikian juga dalam suatu pergelaran dapat diceritakan
bahwa sukma/roh Godayitma dapat menyusup pada seseorang sehingga memiliki sifat
angkaramurka dan ingin menyerang pada kebaikan yang selalu dijunjung tinggi para
Pandawa. Biasanya tokoh yang disusupi oleh Godakumara itu, siapa pun namanya
selalu memihak/membantu para Korawa. Tetapi akhirnya semuanya dapat dikalahkan
oleh Pandawa yang dibantu oleh Anoman dan Prabu Kresna. Cerita-cerita tentang
Godayitma/Godakumara ini merupakan lakon carangan, kelihatannya sudah sulit
diketahui siapa sebenarnya yang pertamakali memiliki sanggit yang demikian.
Tentunya para Dalang dapat dengan bebas menciptakan sanggit-sanggit baru yang
sesuai dengan perkembangan pandangan hidup masyarakat sehingga pergelaran
wayang merupakan sumber inspirasi, menarik dan tetap diminati masyarakat.
Bentuk wayang Prabu Dasamuka, muka sangat garang,
bertaring, bermahkota, berpraba, bersampir, berkain katongan, tangan belakang
irasan. Di sini ditunjukkan empat wayang Dasamuka dan satu wayang Dasamuka
dalam bentuk triwikrama, raksasa berkepala sepuluh. Satu wayang Dasamuka
murgan, artinya matanya nampak hanya satu, jadi miring betul. Dua wayang
Dasamuka nampak kedua matanya, jadi agak miring sedikit. Wanda-wanda dari
wayang Dasamuka antara lain: 1.Begal,
2.Bugis, 3.Iblis, 4.Sembada, 5.Pamuk dan 6.Goteng.
20. BUKBIS.
Gambar-30: BUKBIS
Bukbis disebut juga Pratalamaryam. Ia adalah putra Prabu
Dasamuka dengan Dewi Urangrayung, putri Batara Minalodra di Kandabumi. Ia
memiliki pusaka sebuah topeng yang terbuat dari baja yang disebut "Topeng Waja" dan
berkesaktian, siapa saja yang dipandangnya dengan mata topeng itu akan terbakar
hangus. Saudaranya yang seibu tapi lain ayah, bernama Trigangga/Trihangga,
berwujud kera putih, karena merupakan anak Anoman dengan Dewi Urangrayung.
Bukbis mati pada waktu mengejar Trigangga yang mengambil kembali kendaga yang
berisi Sri Rama dan Lesmana. Pertempuran Bukbis dan Trigangga sangat dasyat,
karena Bukbis menggunakan senjatanya Topeng Waja, siapa pun yang dipandang akan
lebur terbakar. Atas petunjuk Arya Gunawan Wibisana, maka Anoman mempergunakan
kaca raksa untuk memantulkan daya panasnya, sehingga Pratalamaryam mati karena
pandangan mata saktinya memantul kembali terhadap dirinya sendiri.
Bentuk wayang Bukbis yang sebenarnya apakah semacam ini,
tentunya banyak sekali penafsiran, karena pernah terlihat pada suatu pergelaran
wayang yang diselenggarakan di museum ABRI/TMII dan di televisi INDOSIAR dengan
lakon "Topeng Waja",
seorang Dalang yang cukup terkenal, ternyata wayang yang dipergunakan sebagai
Bukbis tidak seperti ini. Ada juga yang menyebut wayang ini sebagai Prabu
Bomantara, atau masih banyak lagi nama-nama yang lain, terutama sebagai
raja-raja tanah seberang. Jadi wayang ini lebih nampak jelas disebutkan sebagai
wayang srambahan.
21.
DASAWILUKRAMA.
Gambar-31: DASAWILUKRAMA
Dasawilukrama
adalah putra Prabu Dasamuka raja Alengka, namun sejak kecil sepeninggal ayahnya
dan serubuhnya negara Alengka diasuh oleh Prabu Ramawijaya dan Dewi Sinta di
Pancawatidenda. Sehingga diajarkanlah ilmu bagaimana orang hidup berbudi luhur,
keperwiraan, kautaman, sehingga bertentangan dari apa yang pernah dilakukan
Prabu Dasamuka ayahnya.
Walaupun Prabu Rama dan Dewi Sinta
mendidiknya dengan ajaran-ajaran kebaikkan, tetapi ternyata Dasawilukrama tidak
seperti apa yang diharapkannya, malahan rasa balas dendam ingin membalas
kematian orang tuanya Prabu Dasamuka untuk membunuh Prabu Rama, timbul dalam
hati kecilnya. Demikian juga Dasawilukrama telah bersekutu dengan kemenakanya raja
Bikukungpura Prabu Beganasura yang putra Raden Indrajit. Karena Prabu Rama
telah lanjut usia, maka ada rencana untuk lengser keprabon, kekuasaan negara
Pancawatidenda akan diserahkan kepada putra angkatnya Dasawilukrama. Rencana
ini telah dirundingkan dengan Narpati Guakiskenda Sugriwa, sehingga semua warga
Pancawatidenda mendengarkan, dan menimbulkan banyak pendapat yang sifatnya
kontroversial, setuju dan tidak setuju. Khususnya para warga wanara sangat
banyak yang tidak setuju, mengingat apabila Dasawilukrama berkuasa akan
semena-mena terhadap para wanara karena yang merubuhkan Alengka adalah para
prajurit wanara ini. Yang nampak seketika itu adalah Jaya Anggada, tanpa ada
panggilan dari Prabu Rama langsung naik ke persidangan menyatakan ketidak
setujuannya atas kebijakan Prabu Rama. Oleh Prabu Rama diputuskan siapa yang
merasa tidak setuju boleh meninggalkan Pancawatidenda. Sehingga Anggada
ditangkap oleh Anoman menyerah dimasukkan tahanan dalam penjara dekat dengan
pesanggrahan Prabu Rama dan Dewi Sinta, sambil menunggu hingga ada keputusan
pengadilan.
Pada suatu malam benar apa yang
terjadi, Dasawilukrama hendak membunuh Prabu Rama dan Dewi Sinta yang sedang
tidur. Namun berkat kewaspadaan Jaya Anggada niat jahat Dasawilukrama dapat
digagalkannya, walaupun Jaya Anggada kena fitnah yang akan membunuh Prabu Rama
dan Dewi Sinta adalah Anggada hingga meninggalkan Pancawatidenda. Jaya Anggada
akhirnya bertemu dengan Raja Bikukungpura Prabu Beganasura yang berniat
membalas dendam ingin menyerang Prabu Rama Wijaya, singkatnya cerita Prabu
Beganasura tewas oleh Jaya Anggada. Pakaian kebesaran Prabu Beganasura
diambilnya dan dipakai untuk menantang Dasawilukrama. Disarankan oleh Prabu
Rama dan seluruh warga Pancawatidenda agar Dasawilukrama sebagai calon pemegang
kekuasaan Pancawatidenda harus dapat menhancurkan Prabu Beganasura.
Dasawilukrama berhadapan dengan Prabu Beganasura yang sebenarnya Jaya Anggada,
sehingga akhirnya tewas melawan Jaya Anggada, maka aman sejahtera para wanara
di Pancawatidenda.
Wayang Dasawilukrama disini
ditafsirkan bermahkota, muka agak tunduk disungging warna merah muda, hidung
dempak, mulut gusen bertaring, mata plelengan, memakai praba, berkain rapekan.
22. PRABU BALADEWA.
Gambar-32: PRABU BALADEWA (SEMBADA)
Gambar-33: PRABU BALADEWA (KAGET)
Gambar-34: PRABU BALADEWA (GEGER)
Gambar-35: PRABU BALADEWA/BEGAWAN CURIGANATA (ZAMAN
PARIKESIT)
Nama lain dari Prabu Baladewa, Kusumawalikita, Balarama,
Basukiyana, Curiganata dan Alayuda. Permaisurinya Dewi Erawati, putri Prabu
Salya raja negara Mandraka. Dengan Dewi Erawati berputra dua orang bernama:
Wisata dan Wilmuka. Prabu Baladewa sangat sakti, karena memiliki senjata pusaka
Nanggala dan Alugora.
Dalam perang Baratayuda Prabu Baladewa memihak Korawa,
karena kesaktiannya, oleh Prabu Kresna dianggap tidak ada tandingnya dan
menyukarkan perlawanan para Pandawa, maka sewaktu perang Baratayuda akan
dimulai Prabu Baladewa dapat disisihkan oleh Sri Kresna, supaya bertapa di
Grojogansewu dengan ditemani oleh putra Sri Kresna yang bernama Setyaka,
sehingga Prabu Baladewa bebas dari dosanya dengan sangsi ditelan bumi. Dalam
pertapaan, suatu hari beliau melihat bahwa warna air terjun semakin lama
semakin bertambah merah bercampur darah dan berbau amis serta banyak puntungan
kereta, roda kereta, senjata dan mayat yang hanyut. Maka ditanykanlah pada
Setyaka, apakah perang Baratayuda sudah dimulai. Oleh Setyaka diberitahukan,
bahwa hal itu disebabkan adanya bencana banjir yang melanda pemukiman penduduk.
Tetapi setelah Batara Narada datang memberitahukan bahwa perang Baratayuda
sedang berjalan dan hampir selesai, maka marahlah Prabu Baladewa dan dikejarnya
Setyaka. Namun dapat dilerai oleh Batara Narada dan dinasehatkan bahwa beliau
diwenangkan melihat perang Baratayuda babak yang terakhir, yaitu bertandingnya
Prabu Suyudana melawan Raden Werkodara. Pada waktu itu Prabu Suyudana telah
terdesak oleh Raden Werkodara, sehingga lari dan mencebur ke dalam kedung
sungai bersembunyi. Pada saat para Pandawa menunggui di sekitar kedung, datanglah
Prabu Baladewa yang menuntut kepada Prabu Kresna mengapa tidak diberitahukan
tentang perang Baratayuda. Semuanya dijelaskan Prabu Kresna dan diberitahukan
bahwa perang Baratayuda yang terakhir masih ada, yaitu perangnya Prabu
Suyudana/Duryudana melawan Raden Werkodara, di mana Prabu Suyudana masih
bersembunyi dalam kedung. Maka dipanggillah Prabu Suyudana oleh Prabu Baladewa
yang semula memang akan memihak Korawa, maka keluarlah Prabu Suyudana begitu
medengar panggilan itu, mengira akan dibantu oleh Prabu Baladewa. Maka
dilanjutkanlah Perang tanding keduanya dengan perang gada, di sinilah gugur
Prabu Duryudana oleh gada Raden Werkodara, dan selesailah perang Baratayuda
dengan kemenangan di pihak Pandawa. Demikian lakon perang Baratayuda dalam
kaset rekaman wayang yang dibawakan oleh seorang Dalang yang sudah cukup
terkenal. Menurut cerita dari mulut ke mulut, lawan tanding Prabu Baladewa
adalah Raden Atareja, tetapi ia telah disisihkan juga oleh Prabu Kresna,
yaitu supaya menjilat bekas tapak kakinya
sendiri sehingga mati sebelum perang Baratayuda dimulai. Selesai perang Baratayuda
Prabu Baladewa kembali ke negara Astina dan mengetahui bahwa Korawa
telah habis tewas di medan perang. Kemudian Prabu Baladewa ikut para Pandawa
sampai zaman Prabu Parikesit naik takhta. Dalam lakon "Jumenengan
Prabu Parikesit", Prabu Baladewa masih tampil di medan perang menghadapi Prabu
Ajibarang yang bermaksud merebut takhta kerajaan Astina. Meskipun sudah berusia
lanjut, ia dapat membunuh Prabu Ajibarang dengan senjata Nanggalanya yang
sangat ampuh itu.
Wayang Prabu Baladewa bermata kedelen, muka disungging
warna merah, bermahkota, berjamang tiga susun, bergaruda membelakang, berpraba,
bergelang, berpontoh, berkeroncong dan berkain katongan. Sebagai ilustrasi
ditampilkan satu wayang yang berkain rapekan, karena zaman pemerintahan Prabu
Parikesit, merupakan akhir dari zaman purwa dan awal dari zaman madya.
Beberapa wanda dari wayang Prabu Baladewa: 1.Geger,
2.Kaget, 3.Sembada, 4.Paripaksa, 5.Rayung, 6.Jago, 7.Banteng dan mungkin masih
banyak lagi. Pernah terlihat wayang Prabu Baladewa wanda Sembada di museum
SENAWANGI Jakarta Kota, wayang tersebut sangat bagus sekali, penyunggingannya
sangat sederhana namun nampak indah sekali.
Gambar-147: GUNUNGAN BLOMBANGAN
Gambar-148: GUNUNGAN BLOMBANGAN
Gambar-149: GUNUNGAN BLOMBANGAN
Gambar-150: GUNUNGAN BLOMBANGAN
Gambar-151: GUNUNGAN BLOMBANGA
Gambar-152: CONTOH SUNGGINGAN DI BALIK GUNUNGAN
BLOMBANGAN
Gunungan disebut
juga Kayon, yang artinya pepohonan. Jika ditinjau dari bahasa Arab "khayyu"
berarti hidup, jadi Gunungan melambangkan bentuk kehidupan yang terdapat di
dalam jagad raya (dunia) yang mengalami tahapan. Demikian menurut S.Haryanto
dalam Bayang Bayang Adiluhung. Untuk uraian dengan pendekatan filsafati tidak
dijelaskan di sini, karena hal yang demikian merupakan suatu bidang khusus. Di
sini hanya ditunjukkan Gunungan sebagai wayang simpingan dan kegunaannya di
pakeliran. Gunungan pada wayang kulit purwa gaya Surakarta dan mungkin juga
pada gagrag Yogyakarta dan gagrag lainnya, menurut jenisnya ada dua macam,
yaitu Gunungan laki-laki disebut juga Gunungan "Gapuran"
dan Gunungan Perempuan disebut juga Gunungan "Blombangan".
Jumlah Gunungan
yang ada dalam satu kotak wayang kulit paling tidak tersedia satu buah
Gunungan. Walaupun ada pula yang diperlengkapi dengan dua/tiga atau lebih.
Namun banyak juga para Dalang (khususnya para Dalang yang sudah cukup terkenal)
membawa satu atau dua Gunungan milik sendiri yang disimping juga di kelir
sehingga dapat menambah indahnya pakeliran. Jika hanya diperlengkapi dengan
satu Gunungan, maka Gunungan tersebut disimping ditancap di tengah-tengah kelir
secara tegak pada saat pakeliran belum dimulai, namun sesudah pakeliran dimulai
Gunungan tersebut diangkat dan ditancap di simpingan kiri atau kanan. Jika
diperlengkapi dengan dua Gunungan biasanya kedua-duanya disimping ditancap
tegak di tengah-tengah kelir ditumpuk menjadi satu dengan Gunungan Gapuran di
depan atau di luar menjadi satu dengan Gunungan Blombangan. Setelah pakeliran
dimulai kedua Gunungan tersebut dicabut, kemudian ditancap di simpingan kanan
untuk Gunungan Gapuran, di simpingan kiri untuk Gunungan Blombangan. Jika
Gunungan jumlahnya tiga, satu ditancap tegak ditengah-tengah kelir, dua
ditancap di simpingan kiri dan kanan. Kalau pakeliran dimulai terserah pada Ki
Dalang di sebelah mana Gunungan yang di tengah-tengah kelir akan dicabut dan
ditancapkan dapat di sebelah kiri, dapat juga di sebelah kanan. Jika jumlah
Gunungan empat, Gunungan tersebut ditancap dua di tengah-tengah kelir, satu di simpingan
kiri, satu di simpingan kanan. Apabila pakeliran dimulai dua Gunungan yang di
tengah-tengah kelir dicabut oleh Ki Dalang dan ditancapkan satu di simpingan
kiri, satu lagi di simpingan kanan.
Beberapa
perbedaan antara Gunungan laki-laki atau Gapuran dan Gunungan perempuan atau
Blombangan terletak pada ornamen gambar yang terisi dalam Gunungan tersebut.
Untuk Gunungan Gapuran di dalamnya dilukiskan sebuah rumah joglo yang nampak
tiang beserta ompaknya, pintu, lantai marmer, tembok batu bata di kiri kanan,
di depan dijaga dua patung raksasa yang membawa perisai dan gada. Patung ini
disebut Cingkarabala dan Balaupata. Di atas rumah joglo, ada dua binatang yang
berhadapan yaitu banteng di sebelah kanan dan harimau di sebelah kiri. Untuk
Gunungan Blombangan di sini tergambarkan sebuah telaga yang nampak ikan di
dalamnya. Di bawah telaga terlukis bermacam-macam binatang seperti: ular,
harimau, gajah, kijang, celeng/babi hutan, burung merak dan sebagainya. Selain
bermacam-macam jenis binatang ada juga yang diisi mangkaran besar, semua ini
tergantung pada selera sipembuat Gunungan Blombangan tersebut. Di dalam buku
ini ditunjukkan satu Gunungan
Blombangan yang dilukiskan gambar/ornamen singa terbang,
sehingga tidak semua orang dapat memahami maksud dari gambar tersebut. Karena
binatang-binatang yang terlukiskan di dalam Gunungan mestinya berupa satwa yang
memang ada atau pernah ada di Nusantara ini, khususnya di pulau Jawa. Namun
karena wayang Gunungan Blombangan ini diperoleh dari seorang penatah wayang yang
mungkin mengambil blak/pola dari orang lain yang kemungkinan besar bukan orang
Indonesia, maka di bawah telaga Gunungan Blombangan ini terlukis gambar singa
terbang.
Di atas telaga
nampak dua ekor garangan atau musang yang berhadapan. Namun atas dasar suatu
kreasi di sini ditunjukkan satu Gunungan Blombangan yang di atas telaga
dilukiskan dua ekor harimau yang sedang dililit ular, hal ini dilakukan atas
dasar pertimbangan memberikan keberagaman Gunungan Blombangan ini. Apakah
dengan demikian dapat lebih memberikan keindahan, tentunya semuanya tergantung
pada penilaian para Dalang, para pakar seni kriya wayang, para pencinta wayang
dan masyarakat pewayangan.
Ada juga yang
menyebutkan bahwa perbedaan antara Gunungan Gapuran dan Gunungan Blombangan
terletak pada bentuknya. Gunungan laki-laki agak meruncing, sedangkan Gunungan
perempuan agak melebar bagian bawahnya atau mblenduk (bahasa Jawa). Demikian
beberapa perbedaan antara Gunungan laki-laki dan perempuan. Adapun persamaannya
kedua-duanya berisikan gambar garuda kiri/kanan, ada juga yang menyebut
bledekan. Kedua-duanya terlukiskan satu pohon di tengah-tengah dengan cabang,
ranting, dedaunan, bunga-bunga dan buah-buahan secara simetris. Di dalam
pepohonan tersebut terdapat bermacam-macam satwa jenis unggas seperti burung
merak, tekukur, enggang, ayam hutan dsb, di samping satwa jenis monyet, lutung
(monyet hitam). Pada batang pohon dilukis dua mangkaran secara tersusun.
Mangkaran tersebut ada yang bermata satu, ada juga yang bermata dua, di sini
ditunjukkan bermata dua. Untuk Gunungan perempuan ada kalanya dilukiskan
mangkaran yang diletakkan di bawah telaga. Sedangkan di balik kedua jenis
Gunungan tersebut dilukiskan suatu mangkaran besar dengan di atasnya dilukiskan
api yang menyala berwarna merah kekuning-kuningan, atau disungging angin yang
bertiup kencang diberi warna abu-abu kekuning-kuningan, atau biru. Gambar ini
sebenarnya tergantung selera pembuatnya,
pernah terlihat Gunungan Gapuran milik seorang Dalang yang cukup terkenal di
baliknya disunggingkan candi Prabanan. Demikian beberapa ornamen yang umum ada pada Gunungan laki-laki dan
perempuan pada wayang kulit purwa gaya Surakarta. Adapun makna dari pada
ornamen dalam kedua jenis Gunungan tersebut telah banyak diuraikan oleh para
pakar, oleh karena itu tidak diuraikan dalam buku ini.
Gunungan yang
ditancap di simpingan kanan biasanya Gunungan Gapuran. Karena saat pakeliran
dimulai/jejer (bahasaJawa), sang raja selalu ditancapkan di sebelah kanan,
sedangkan para menteri, maha patih, para brahmana, para tamu agung dan keluarga
raja selalu ditancap di sebelah kiri berhadapan dengan sang raja. Dengan
demikian nampak di belakang sang raja pandangan dalam Gunungan yang berisikan
gambar rumah atau istana.
Sedangkan
Gunungan perempuan selalu ditancap di simpingan kiri. Hal ini sangat memudahkan
untuk membuat adegan seorang ksatria yang sedang berkelana akan memasuki hutan
(dalam pakeliran selalu jalan dari kanan ke kiri), maka dihadapan ksatria
tersebut ditancapkan Gunungan perempuan yang diangkat dari simpingan kiri.
Karena Gunungan perempuan berwujud telaga, pohon dan satwa hutan, maka tepatlah
untuk menggambarkan suasana hutan yang lebat, gawat, wingit dan angker,
demikian sering diucapkan oleh Ki Dalang di pakeliran. Namun benar dan salahnya
dikembalikan pada para pembaca, karena pendapat yang demikian hanya merupakan
kesan pribadi seorang penggemar wayang dan pergelarannya. Adapun secara umum
Gunungan dapat dimanfaatkan sebagai istana baik pada saat jejer/adegan istana
maupun saat sang raja akan masuk sanggar pemujaan. Gunungan digunakan sebagai
jalan atau jembatan yang rusak akibat bencana alam, ditunjukkan pada waktu
adegan perampogan atau barisan tentara yang siap siaga dengan berbagai macam
senjata terpaksa harus memperbaiki jalan atau jembatan tersebut tanpa merusak lahan pertanian rakyat. Yang
jelas adegan tersebut mencerminkan timbulnya suatu delema antara kepentingan
militer dan bukan militer (pertanian, lindungan lingkungan hidup, transportasi
dsb), di mana dituntut harus diberikan jalan keluar yang paling bijaksana.
Gunungan sebagai
batas adegan di mana Gunungan ditancap kembali di tengah-tengah kelir. Jika
waktu menunjukkan sebelum tengah malam atau iringan gamelan masih dalam patet
enam, maka Gunungan ditancap miring sedikit ke kiri. Kalau menunjukkan tengah
malam atau iringan gamelan sudah masuk patet sembilan Gunungan ditancap tegak.
Sedangkan apabila waktu telah menujukkan dini hari atau menjelang pagi atau
gamelan telah masuk dalam patet manyura, maka Gunungan ditancap condong kekanan
sedikit. Demikian Gunungan sebagai batas adegan yang merupakan salah satu kesan
pribadi seorang pembuat wayang dan pemerhati pergelarannya, sehingga setiap
orang dapat saja memiliki kesan yang berbeda.
Gunungan
digunakan untuk menggambarkan api yang berkobar, angin yang bertiup, lautan
yang bergelora, banjir bandang, hujan lebat, hujan abu, banjir darah, dan
sebagainya. Semua ini ditunjukan dengan cara membalik Gunungan, walaupun
dilihat dari belakang kelir nampak sama tidak ada bedanya. Suasana gelap atau
malam hari dapat ditunjukkan dengan cara menutupkan lampu/blencong.
Gunungan untuk
menunjukkan gunung, pohon, adegan ini sering ditunjukkan saat Anoman atau
Werkodara mencabut dan mengangkat gunung atau pohon, terlihat dalam lakon ”Anoman
Duta”, “Rama Tambak”, “Babat Alas Mertani (Wana Marta)”.
Gunungan untuk
menggambarkan bendungan, dapat dilihat dalam lakon "Rama
Tambak".
Gunungan untuk
menggambarkan telaga/danau, dapat dilihat dalam lakon Subali, Sugriwa dan
Anjani berebut Cupu Manik Astagina. Tentunya Gunungan Blombangan
yang digunakan untuk adegan tersebut, jika Gunungan Blombangan tersedia pada
seperangkat wayang yang disediakan. Semua ini tentunya yang pasti tergantung
selera Ki Dalang, yang hal ini belum tentu sama dengan selera pribadi seseorang.
Gunungan sebagai
tanda pakeliran selesai/penutup atau sering disebut tancep kayon. Setelah
adegan tayungan atau beksan atau jogetan yang dilakukan oleh Raden
Werkodara/Anoman/Batara Bayu kemudian jejer terakhir selesai, pakeliran
kemudian ditutup oleh Ki Dalang dengan menancapkan Gunungan di tengah-tengah
kelir atau di tengah-tengah adegan tersebut dengan iringan gending ayak.
Demikian beberapa
kegunaan, pengertian dan jenis dari Gunungan, adapun kegunaan, pengertian dan
jenis yang lainnya mungkin masih ada. Dengan demikian dalam kelompok wayang
simpingan kanan Gunungan Gapuran tentunya tidak perlu disorot ulang.
Langganan:
Postingan (Atom)